Anak Perempuan yang Membawa Negeri di Pundaknya
Dalam ruang kelas yang terang, ada seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dan sepatu yang terlalu besar. Ia duduk diam di bangku paling belakang, seolah-olah berusaha menghapus keberadaannya dari perhatian dunia. Namanya tidak disebutkan. Tapi kita tahu dia berasal dari tempat yang jauh. Dari negeri yang mungkin hanya dikenali guru lewat berita tentang perang atau migrasi.
Ia adalah satu dari sekian banyak anak yang membawa negeri di pundaknya.
Sekolah selalu digambarkan sebagai tempat yang netral. Datar. Ruang kosong yang menanti diisi ilmu pengetahuan. Tapi sesungguhnya, sekolah tidak pernah sepenuhnya netral. Ia adalah ruang sosial. Ia adalah arena tafsir budaya. Dan bagi anak-anak pengungsi perempuan, ia bisa menjadi tempat paling sunyi atau paling gaduh, tergantung siapa yang menyapa dan siapa yang memilih diam.
Dalam sebuah survei yang dilakukan pada guru-guru sekolah dasar di Inggris, terungkap ada jurang halus antara keyakinan dan tindakan. Banyak guru menyatakan pentingnya isu keberagaman, pentingnya membicarakan ras dan gender sejak dini. Mereka ingin adil. Mereka ingin memahami. Namun, ketika dihadapkan pada kisah nyata seorang anak yang dipanggil "seperti kotoran" oleh teman sekelasnya, responnya menjadi netral, datar, universal. Mereka bilang, “Tidak baik berkata begitu pada siapa pun.” Mereka lupa bahwa bagi sang anak, hinaan itu bukan sekadar kata. Ia adalah sejarah. Ia adalah identitas yang ditolak.
Di ruang-ruang kelas Inggris, integrasi dan asimilasi seperti dua kata yang berdansa dalam senyap. Asimilasi menuntut anak-anak ini melepas bahasa ibunya di gerbang sekolah. Integrasi mengajak mereka membawa kisah leluhur ke meja belajar. Dua gagasan ini bukan hanya teori sosiologis. Mereka hidup dalam keputusan-keputusan kecil: apakah seorang guru meminta anak itu bercerita tentang negaranya? Ataukah menyuruhnya diam dan belajar seperti anak-anak lainnya?
Dalam survei itu, mayoritas guru cenderung berpihak pada integrasi. Mereka menganggap bahwa menjadi bagian dari komunitas tidak harus menanggalkan akar. Ini kabar baik. Tapi kita tahu, dalam praktik, pilihan-pilihan pedagogis tidak selalu setia pada ideologi. Ada bias yang menyelinap dalam kalimat-kalimat lembut. Ada ketakutan untuk salah bicara. Maka lebih mudah menyapu semua perbedaan ke bawah permadani universalitas.
Tapi anak-anak tahu. Mereka merasakan kapan diri mereka diakui, dan kapan mereka disamarkan menjadi "anak-anak pada umumnya."
Satu hal yang muncul dengan kuat dari penelitian ini adalah ketulusan para guru. Mereka ingin hadir secara emosional. Mereka merasa dekat dengan murid-muridnya. Tapi kedekatan emosional bukan jaminan pemahaman sosial. Seperti seorang ibu yang memeluk anaknya namun tak tahu bahwa pelukan itu menyakiti karena menyentuh luka yang belum sembuh.
Para guru dalam survei itu mengaku tidak cukup dilatih untuk menangani keterampilan sosial-emosional, apalagi ketika konteksnya adalah trauma migrasi. Mereka tahu pentingnya, tapi tidak tahu cara mengenalinya. Seorang anak yang diam bisa dianggap pemalu, padahal mungkin sedang memendam mimpi buruk tentang kamp pengungsian. Seorang anak yang mudah marah bisa dianggap nakal, padahal mungkin sedang bergumul dengan kehilangan yang tak sempat dikubur.
Apa artinya menjadi guru dalam dunia yang berpindah? Apakah cukup menjadi penyampai kurikulum, ataukah ia harus menjadi pelintas batas, antara budaya, antara bahasa, antara luka dan harapan?
Saya membayangkan seorang guru duduk di hadapan muridnya. Ia tahu bahwa di balik seragam sekolah itu ada tubuh kecil yang memanggul dua dunia: satu dunia yang ditinggalkan, satu lagi yang belum sepenuhnya menerima. Ia tahu bahwa tugasnya bukan menghapus dunia pertama agar dunia kedua bisa masuk. Tapi menjahit keduanya menjadi satu jubah yang bisa dikenakan anak itu dengan bangga.
Ada guru yang berkata, “Aku akan minta dia bercerita tentang negerinya.” Kalimat ini, sesederhana apapun, bisa menjadi pintu bagi anak itu untuk merajut kembali identitasnya. Tapi tidak semua guru berkata begitu. Ada pula yang ingin melaporkan ayah si anak ke otoritas hanya karena konflik identitas. Di situlah kita tahu: kebaikan bukan sekadar niat, tapi kebijaksanaan untuk menunda penilaian.
Dalam kelas yang penuh dengan perbedaan, apa yang bisa menjadi benang pengikat? Jawabannya bukan hanya kurikulum, tapi cara guru melihat. Melihat bukan dengan mata, tapi dengan batin yang terbuka. Karena luka sosial tidak selalu berdarah, tapi ia menetap di cara anak-anak berjalan, berbicara, atau memilih duduk sendiri.
Maka tugas guru hari ini adalah menjadi pembaca isyarat. Isyarat-isyarat halus yang ditulis dalam diam anak-anak pengungsi. Dalam tatapan kosong anak perempuan yang baru sebulan di negeri ini. Dalam cara mereka menyebut nama sendiri, dengan aksen yang pelan-pelan terkikis demi bisa diterima.
Esai ini tidak ingin menyalahkan siapa pun. Tapi ingin menunjukkan bahwa kebaikan hati saja tidak cukup. Niat baik harus ditemani oleh pelatihan yang dalam, oleh keberanian untuk melihat kenyataan yang tak selalu nyaman. Bahwa dalam upaya mengajarkan "kebaikan universal", kita kadang lupa bahwa pengalaman manusia itu partikular. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan plester yang sama.
Ada anak yang membutuhkan ruang untuk menangis dalam bahasa ibunya. Ada yang ingin tahu bahwa menjadi berbeda bukan kutukan. Ada yang hanya ingin sekali saja, dalam hidupnya, didengarkan sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai simbol dari negara yang jauh.
Dan mungkin, pendidikan yang sejati adalah ketika seorang guru, di tengah hiruk pikuk administrasi dan target kurikulum, sempat bertanya: “Apa yang kamu rindukan hari ini?” Bukan karena itu bagian dari pelajaran, tapi karena itu bagian dari menjadi manusia.
Sebab mengajar, pada akhirnya, bukan sekadar memindahkan ilmu. Tapi menemani jiwa-jiwa kecil menyeberang dari ketakutan menuju pengakuan. Dari perbatasan menuju rumah.
Dan mungkin, hanya mungkin, dari kelas kecil itulah dunia yang lebih ramah mulai dijahit, oleh tangan-tangan yang masih belajar menulis.

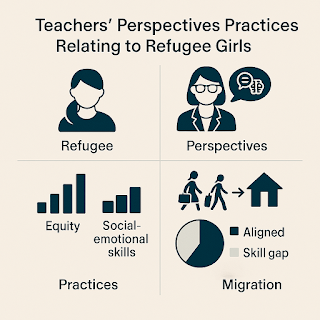

Posting Komentar